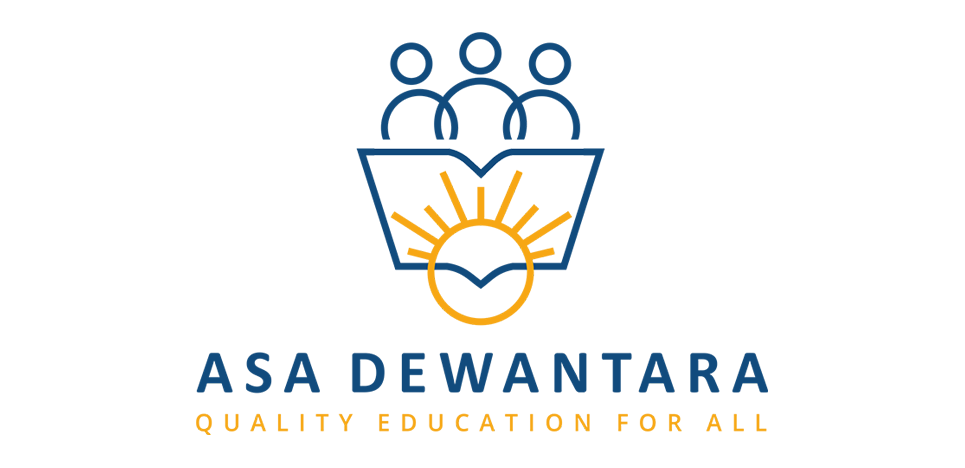Praktik pendidikan Indonesia saat ini dinilai semakin menjauh dari pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara yang menempatkan siswa sebagai subyek yang selaras dengan dunianya.
Sistem pendidikan saat ini dinilai belum berbudaya karena tidak menempatkan budaya sebagai marwahnya, tetapi mengedepankan nilai ekonomi semata. Maka, muncullah beberapa sekolah alternatif sebagai jawaban, tetapi skalanya tidak terlalu besar. Pemerintah didorong untuk mengarusutamakan kebudayaan dalam pendidikan agar nilai-nilainya tidak tergerus zaman.
Hal ini mengemuka dalam diskusi bertajuk ”Mengarusutamakan Kebudayaan dalam Pendidikan” sebagai mata acara Pekan Kebudayaan Nasional 2023 di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Jakarta. Penggagas program Penguatan Karakter Siswa Mandiri melalui Kreasi Seni (Presisi), Ibe Karyanto, mengatakan, praktik pendidikan saat ini semakin menjauh dari pandangan filosofis Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menempatkan siswa sebagai subyek yang selaras dengan dunianya.
Pendidikan saat ini lebih berorientasi kebutuhan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan siswa diukur sebagai keluaran yang dapat memenuhi kebutuhan korporasi. Pada akhirnya siswa hanya menjadi obyek penerima informasi atau pengetahuan dari guru alias tidak terlibat dalam proses pembelajaran tersebut.
”Kenapa kita sekarang, setelah sekian dekade berpisah dengan Ki Hajar Dewantara, gelisah untuk mengarusutamakan kembali kebudayaan dalam pendidikan. Ini sama dengan pendidikan kita saat ini memang tidak berkebudayaan, atau setidak-tidaknya arus kebudayaan dalam pendidikan itu terhambat,” kata Ibe, Rabu (25/10/2023).
Menurut Dewan Kurator Pekan Kebudayaan Nasional (PKN) 2023 ini, pendidikan alternatif atau yang dalam sistem pendidikan disebut sekolah nonformal juga belum menyentuh akar masalah. Sebab, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 juga belum secara spesifik membedakan sistem pendidikan formal dan nonformal, baik secara kurikulum maupun administrasi. Yang membedakan hanya waktu dan tempatnya saja.
Namun, upaya untuk membuat pendidikan yang berkebudayaan ini menemui sejumlah hambatan. Hal itu di antaranya sekolah yang tidak lagi berdaulat karena terkungkung pada orientasi hasil tes Programme for International Student Assessment (PISA). Setiap kali skor PISA keluar, pemerintah langsung merespons dengan melakukan perubahan dalam pendidikan, termasuk mengganti kurikulum. Padahal, PISA mengabaikan keadaan dunia konkret di sekitar.
”PISA tidak salah, tetapi tidak lengkap karena ukurannya sangat materialistik. Kalau memang punya keprihatinan kebudayaan dalam arus utama pendidikan, maka tambahkanlah item penilaian di dalam PISA itu yang tidak dimiliki oleh Eropa yang menjadi kekhasan budaya kita,” ucapnya.
PISA adalah program evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk mengukur kemampuan siswa berdasarkan tiga bidang, literasi matematika, literasi membaca, dan literasi sains; serta mengevaluasi sistem pendidikan suatu negara. Skor PISA 2018, dari sekitar 80 negara di dunia yang mengikuti program ini, pendidikan di Indonesia berada di posisi ke-74 alias peringkat enam dari bawah.
Pertukaran pengetahuan
Monika Irayati dari Presidium Jaringan Pendidikan Alternatif juga menilai orang dewasa atau guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu bagi siswa. Proses belajar-mengajar sejatinya adalah pertukaran pengetahuan di antara keduanya.
”Pandemi Covid-19 telah membuktikan sistem pendidikan kita terlalu meletakkan guru sebagai aktor utama dalam pendidikan. Begitu gurunya terputus, anaknya tidak bisa belajar. Pemerintah perlu belajar dari pendidikan alternatif ini,” kata Monika.
Selain itu, lanjut Ibe, sistem pendidikan nasional sangat teknokratik dan birokratik. Pengajar dan program pendidikan terlalu banyak disibukkan dengan urusan teknis dan administratif birokrasi daripada substansi untuk melibatkan siswa dalam dunianya. Ini harus diubah.
Oleh karena itu, pemerintah perlu mengubah atau mempertegas paradigma pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara yang menekankan pendidikan kontekstual yang berpusat pada anak. Setiap siswa harus dilibatkan dalam pengalaman hidup sehari-hari agar mereka mampu melihat permasalahan di sekitar.
”Biarkan anak merdeka mengenali lingkungannya. Dalam paradigma ini kita lebih berorientasi pada proses dan mengukur output itu dari dampaknya. Kalau diukur dari lulus ujian itu hanya teknis, bukan dampak dari setiap alumnus atau lulusan pendidikan di masyarakat,” tutur Ibe.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikbudristek Zulfikri Anas pun mengamini hal ini. Setiap siswa seyogianya harus merdeka dari kebodohan dan kemiskinan, serta merdeka dari jeratan kapitalisme dan kungkungan administrasi birokrasi dunia pendidikan.
Menurut Zulfikri, Kurikulum Merdeka yang digagas Mendikbudristek Nadiem Makarim telah memberikan keleluasaan bagi pendidik dan sekolah agar menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik. Kurikulum ini fokus pada pengembangan soft skill dan karakter dengan materi belajar yang esensial dan fleksibel, baik bagi guru maupun siswanya.
”Kurikulum Merdeka ini kami rancang kerangkanya secara nasional agar bisa diterapkan dalam situasi seminim apa pun dan di mana pun. Syaratnya cuma dua, murid dan gurunya ada, karena guru tidak akan ada kalau muridnya tidak ada. Di mana muridnya ada kami wajib memberikan pelayanan,” kata Zulfikri.
Sejak diterapkan pada 2020, Kurikulum Merdeka sudah diterapkan di 293.371 satuan pendidikan. Rinciannya, 101.313 di tingkat PAUD/TK/KB, 130.648 SD/sederajat, 34.551 SMP/sederajat, dan 11.222 SMA/sederajat.
Sumber: Kompas.id