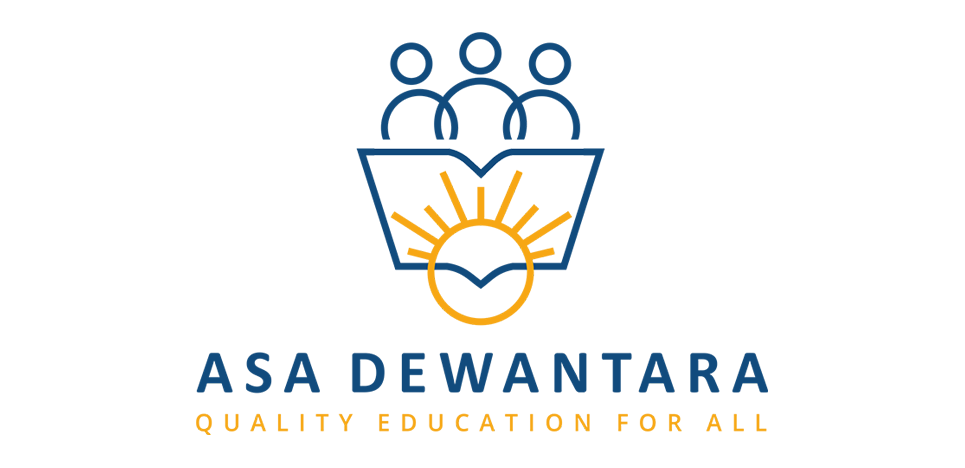Dengan dijadikannya rasionalitas ekonomi sebagai filosofi dasar pendidikan, maka iapun menjadi parameter yang membatasi wacana untuk mencari pemecahan krisis tadi sekaligus menjadi rujukan dan ideal untuk melakukan perombakan sistem pendidikan. Dalam konteks ini pulalah kalangan bisnis dan pendidikan seolah menemukan partnership baru untuk bersama-sama merumuskan tujuan-tujuan pendidikan.
Pendidikan Nasional kembali menjadi sorotan. Pembicaraan berkisar dalam prioritas pembangunan bangsa, pilihan kebijakan dan pelaksanaannya, sampai pada falsafah pendidikan itu sendiri. Yang seringkali hilang dalam banyak diskusi ini adalah bagaimana rasionalitas ekonomi menjadi parameter yang membatasi ruang lingkup diskusi mengenai pendidikan nasional dengan segala masalahnya.
Menarik untuk disimak bahwa rasionalitas ekonomi untuk beberapa waktu juga menjadi parameter diskusi mengenai pendidikan di Amerika Serikat, suatu negara yang jelas menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda dengan Indonesia. Ada baiknya kita belajar dari debat yang berkembang di Amerika Serikat.
Ketidaksiapan para lulusan sekolah kita di semua jenjang pendidikan telah menjadi penjelasan standar atas ketidakmampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ia juga menjadi alasan standar bagi produktivitas yang rendah yang berakibat pada lemahnya daya saing dunia industri Indonesia dibanding negara-negara lain. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus diarahkan untuk menyiapkan siswa untuk segera bisa bekerja di berbagai sektor industri. Pembicaraan mengenai kebijakan pendidikan akhir-akhir ini harus selalu dibarengi dengan peringatan “kalau kita mau berperan dalam perekonomian global”.
Wacana (disclourse) tentang pendidikan yang serupa juga sangat dominan di Amerika Serikat sejak masa kepresidenan Reagan, berlanjut dengan Bush dan terus berlangsung dalam era Republican Revolution yang dipelopori Newt Gingrich.
Sebagai Filosofi Dasar?
Laporan-laporan berbagai institusi prestisius seperti National Commission on Excellence in Education dan National Task Force on Education for Economic Growth pada kurun waktu ini berkesimpulan bahwa bangsa Amerika berada dalam situasi yang gawat dan diambang kehancuran ekonomi. Semua ini disebabkan oleh kualitas yang buruk dari sistem pendidikan. Yang mencolok kemudian adalah upaya untuk mengaitkan situasi ekonomi Amerika—dalam hal ini dinamika ekonomi dalam negeri yang kendor dan merosotnya daya saing dalam pasar luar negeri yang berakibat pada naiknya tingkat pengangguran dan hilangnya banyak lapangan kerja tradisional—dengan kegagalan sekolah untuk mendidik dan menyiapkan siswa untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat luas (baca: sektor industri).
Dengan pengkaitan hubungan tadi, maka filosofi dasar pendidikan pun digulirkan ke arah rasionalitas ekonomi. Keberhasilan sekolah pun dilihat sebagai usaha untuk menyelamatkan “keunggulan berkompetisi dalam pasar dunia yang semakin menipis”. Sistem pendidikan yang ada dianggap sebagai tidak mampu mendidik anak sesuai persyaratan lapangan kerja kini, apalagi lapangan kerja masa depan.
Selanjutnya, dengan dijadikannya rasionalitas ekonomi sebagai filosofi dasar pendidikan, maka iapun menjadi parameter yang membatasi wacana untuk mencari pemecahan krisis tadi sekaligus menjadi rujukan dan ideal untuk melakukan perombakan sistem pendidikan. Dalam konteks ini pulalah kalangan bisnis dan pendidikan seolah menemukan partnership baru untuk bersama-sama merumuskan tujuan-tujuan pendidikan. Bersama-sama mereka menyarankan macam-macam pengetahuan dan keterampilan yang penting untuk diajarkan di sekolah. Pada umumnya pelajaran-pelajaran mana yang penting ditentukan berdasarkan evaluasi atas besar sumbangan mata pelajaran tadi terhadap pengembangan teknologi tinggi mendapatkan kedudukan yang penting.
Menambah Krisis Sebenarnya
Sampai di sini barangkali dahi kita berkerut oleh persamaan luar biasa dalam batasan masalah dan resep pemecahan yang ditawarkan untuk Indonesia dan Amerika Serikat, dua negara yang barangkali berbeda dalam aspek yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, setelah kita untuk sementara bisa menerima “penyamaan” ini, adalah apakah rasionalitas ekonomi benar-benar mewakili masalah yang ada.
Banyak tokoh pendidikan Amerika yang memberikan reaksi terhadap kecenderungan di atas. Diantaranya yang paling vokal adalah Henry Giroux dan Stanley Aronowitz (Education Undersiege, 1984 dan Education Still Undersiege, 1994). Mereka berargumentasi bahawa kecenderungan ini pertama-tama telah salah merepresentasikan krisis di dalam dunia pendidikan di AS dan oleh karenanya menawarkan pemecahan yang salah pula. Masalah meningkatnya pengangguran, menurunnya produktivitas, dan inflasi hampir taka da hubungannya dengan masalah mutu pendidikan berteknologi tinggi. Hal-hal seperti larinya modal, kurangnya visi, kurangnya perencanaan, dan sebangsanya, dalam dunia industri di Amerika perannya lebih besar dalam menciptakan kekusutan ekonomi belakangan ini. Di samping itu, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar lowongan pekerjaan yang tercipta (selama lebih dari sepuluh tahun ini, sejak 1983 setidaknya) adalah untuk pekerjaan-pekerjaan industri jasa tingkat rendah yang tak memerlukan keahlian, sementara lowongan pekerjaan dalm teknologi tinggi porsinya sangat kecil.
Lebih menyedihkan lagi, menurut Giroux dan Aronowitz, falsafah rasionalitas ekonomi ini justru yang menambah parah krisis sebenarnya dalam dunia pendidikan. Menurut mereka falsafah ini gagaltidak hanya dalam sistem pendidikan tapi juga dalam ketidakmampuannya untuk menyediakan visi yang secara serius mempertimbangkan partisipasi dalam kehidupan social dan politik sebagai hal yang diharapkan dari setiap warga negara dalam masyarakat yang demokratis. Terlebih lagi falsafah semacam ini telah meletakkan tekanan yang tidak pada tempatya pada pertimbangan-pertimbangan yang terlalu spesifik dan teknikal. Dengan kata lain falsafah semacam ini telah meremehkan peran pengembangan ruang-ruang sosial di mana siswa dapat belajar dan mempraktikkan keterampilan-keterampilan berpartisipasi secara demokratis dalam proses-proses politik, sosial, dan budaya.
Yang terdesak ke belakang dalam wacana rasionalitas ekonomi adalah tujuan pendidikan untuk mengembangkan manusia yang bernalar kritis dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Mata pelajaran seperti sejarah, civic, multikulturalisme, dan sebagainya dianggap tidak penting, toh dalam dunia bisnis/industri pengetahuan dalam hal ini tak akan ditanyakan dalam formulir lamaran kerja. Bagi Giroux dan Aronowitz, hal inilah yang justru menunjang berkembangnya krisis yang sekarang dihadapi bangsa Amerika, yaitu krisis dalam pengembangan pengertian akan peran dan tanggung jawab sebagai warga sebuah negara demokrasi. Perwujudan dari krisis ini antara lain adalah semakin terlibatnya anak-anak usia sekolah pada tindak-tindak kriminal yang kuantitas maupun kualitasnya semakin hari semakin meningkat.
Barangkali memang ada tujuan pendidikan universal yang bisa berlaku baik di Amerika maupun di Indonesia. Namun rasanya tujuan pendidikan yang didasarkan pada rasionalitas ekonomi bukan salah satunya. Sebaliknya tujuan pendidikan untuk mengembangkan manusia bernalar kritis dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga suatu negara, suatu masyarakat, suatu kelompok, suatu keluarga, telah banyak disuarakan oleh tokoh-tokoh berwibawa dalam masyarakat kita (Lihat komentar Prof. Dr. Fuad Hassan dan tulisan Y.B Mangunwijaya dalam Kompas, 14 dan 15 Mei 1996).
Kita memang harus mampu melihat kaitan pendidikan dengan ekonomi, namun tanpa membuat siswa sebagai sekadar sumber daya dalam konteks sempit dunia bisnis dan industri. Dapatkah kita terima bila tujuan-tujuan pendidikan dirumuskan dan hasilnya dievaluassi oleh kalangan industri dan bisnis? Ada kekhawatiran bahwa dengan begitu pendidikan cenderung, walaupun secara tidak langsung, diarahkan untuk menghasilkan karyawan-karyawan yang terampil dan penurut, yang bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan, terutama, perlakuan perusahaan, sekaligus buta hukum, khususnya hukum perburuhan. Selain itu sekolah lantas sekadar merupakan job training yang mestinya memang harus disediakan oleh perusahaan-perusahaan. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan tadi mendapatkan pool tenaga kerja yang sudah terlatih tanpa harus mencari dan tanpa komitmen serius untuk mengontrak.
Hal lain yang lebih mendasar adalah hubungan pendidikan dengan kebutuhan negara dan bangsa yang lebih luas. Dalam mewujudkan masyarakat demokrasi Indonesia memerlukan manusia-manusia yang sadar hukum, politik, serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sekolah dalam hal ini merupakan institusi penting yang dapat berperan sebagai “ruang social” di mana siswa mengembangkan keterampilan hidup berdemokrasi. Hal ini semakin terasa pentingnya dengan semakin banyaknya lulusan-lulusan sekolah lanjutan muda usia yang bekerja di pabrik-pabrik. Mereka perlu tahu bagaimana caranya berunjuk rasa secara demokratis, sehingga sebagai karyawan nantinya mereka bisa mengajukan tuntutan dengan damai, tidak beringas, apalagi menimbulkan kekacauan.
Di sisi yang lain tentunya sekolah bisa “menyiapkan” mereka untuk sadar bawah hak-hak mereka sebagai karyawan kelak dijamin dan dilindungi oleh hukum perburuhan. Perkelahian massal, pengeroyokan, dan peristiwa Ujung Pandang belakangan ini menunjukkan betapa perlunya siswa dan mahasiswa belajar, melihat, dan mempraktikkan cara-cara berunjuk rasa dan menuntut hak secara demokratis yang tenteram dan damai. Demikian pula, apparat keamanan (yang sebelumnya tentunya adalah pelajar dan/atau mahasiswa juga) perlu belajar, melihat, dan mempraktikkan cara-cara “mengendalikan” pengunjuk rasa secara demokratis pula. Semoga saja.
Ditulis Oleh: Abdul Malik Gismar
*) dipublikasikan pertama kali di Media Indonesia edisi Rabu, 12 Juni 1996